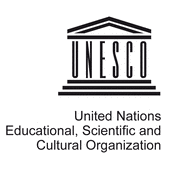Property:Description id
From BASAbaliWiki
D
Sendratari Dewi Kunti - Suluh Ibu Sejati disarikan dari cerita epik pewayangan Maha Barata di mana peran Dewi Kunti diangkat sebagai suluh dan tauladan dari seorang ibu tunggal yang berhasil membesarkan, mendidik dan membimbing ke 5 Putra Pandawa menjadi ksatria yang berbudi luhur, rendah hati, mengabdi kepada rakyat dan berbakthi kepada orang tua, ibunda terkasih Dewi Kunti.
Sendratari Dewi Kunti - Suluh Ibu Sejati diciptakan dan diproduksi oleh Deniek G. Sukarya sebagai penggagas ide, sutradara, penulis naskah dan jalan ceritra. Sendratari ini juga untuk pertama kali memanfaat kayonan sebagai simbol perjalanan dan pergantian waktu untuk pertunjukan di panggung dengan ditarikan dinamis oleh 5 penari. Untuk pertama kali juga, Palawakia yang menjelaskan tentang kisah cerita ini dibawakan dalam dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Bali kuno yang biasa dipakai dalam pewayangan hingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas.
Sendratari ini telah dipentaskan di 3 acara spesial: Dharma Shanti Propinsi Banten 2012 di Serang, rangkaian acara HUT Taman Mini Indonesia Indah untuk mewakili Anjungan Bali, dan pementasan khusus dengan dinner masakan Bali di Garden the Sultan Hotel Jakarta. +
Musik-musik Navicula dipengaruhi genre alternatif rock era 90 an, yang dipopulerkan oleh band Nirvana, Pearl Jam, Sound Garden dan Alice in Chains. Secara musikalitas Navicula menggabungkan musiknya dengan warna lain seperti psikedelia, progresif, balada, funk, dan musik etnik-tradisional (world music).
Lagu Dinasti Matahari berkolaborasi dengan Kitapoleng yang mengangkat kembali tarian Sanghyang Jaran, Barong Brutuk, dan beberapa tarian dari budaya suku Nias, Badui, Minahasa dan Papua. Lagu ini adalah bentuk ucap syukur atas apa yang sudah tersedia di alam bagi kehidupan manusia di Indonesia yang diibaratkan sebagai anak-anak matahari.
Lagu ini diluncurkan sebagai perayaan ulang tahun Navicula yang ke 25 tahun dengan formasi band diperkuat oleh Gede Robi (vokal), Dadang Pranoto (gitar), Palel Atmoko (drum), Krisnandha Adipurba (bass) dan dilengkapi lantunan vokal Ida Bagus Subawa. Lagu ini juga melibatkan kolaborasi para produser direktur seperti Sandrina Malakiano, Dibal Ranuh, Jasmine Okubo dan Gede Robi.
"Dinasti Matahari" ini bukan hanya membawa nama Navicula, tapi juga membawa nama Indonesia dengan ragam kekayaan alam dan suku budaya yang tentunya harus dijaga kelestariannya untuk generasi pewaris. +
F
G
Gambuh adalah teater dramatari Bali yang dianggap paling tinggi mutunya dan juga merupakan dramatari klasik Bali yang paling kaya akan gerak-gerak tari, sehingga dianggap sebagai sumber segala jenis tari klasik Bali.
Diperkirakan Gambuh muncul sekitar abad ke-15 dengan lakon bersumber pada cerita Panji. Gambuh berbentuk teater total karena di dalamnya terdapat jalinan unsur seni suara, seni drama dan tari, seni rupa, seni sastra, dan lainnya.
Gambuh dipentaskan dalam upacara-upacara Dewa Yadnya seperti odalan, upacara Manusa Yadnya seperti perkawinan keluarga bangsawan, upacara Pitra Yadnya (ngaben) dan lain sebagainya.
Gambuh Panji mengisahkan percintaan Prabu Lasem dengan Diah Rangke Sari yang merupakan seorang putri Kerajaan Daha. +
Gong kebyar adalah salah satu barungan gamelan Bali berlaras pelog lima nada yang melahirkan ungkapan musikal benuansa kebyar. Gong kebyar menyajikan “tabuh-tabuh kekebyaran” dengan bentuk komposisi yang memainkan seluruh alat gamelan secara serentak dalam aksentuasi yang poliritmik, dinamis dan harmonis. Secara musikal gamelan Gong Kebyar menurut Sugiartha (2008 : 51), adalah sebuah orkestra tradisional Bali yang memiliki perangai keras (coarse sounding ensamble). Konstruksi harmonis yang melahirkan kesatuan perangkat gamelan Gong Kebyar didominasi oleh alat-alat perkusi, ditambah dengan beberapa alat tiup dan gesek. Sebagai gamelan yang berfungsi menyajikan gending-gending pategak (instrumental), mengiringi berbagai jenis tarian maupun dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, Gong Kebyar telah dikenal dan menjadi populer dengan begitu cepat dan mampu menggugah semangat para pencinta gamelan Bali yang menyebar hampir di berbagai belahan dunia.
Gong Kebyar yang diduga muncul pada tahun 1915, memang sudah umum dikenal oleh masyarakat Bali bahkan kini telah dimiliki hampir oleh setiap banjar dan desa di Bali, yang memfungsikan barungan gamelan ini untuk berbagai kepentingan, dari pentas seni yang bersifat presentasi estetik murni, hingga untuk mengiringi upacara ritual keagamaan. I Wayan Rai (2008:7-8) menyebutkan di Bali telah tercatat tidak kurang dari 1.600 barung gamelan Gong Kebyar tentu jumlah ini kian bertambah. Gamelan ini ada yang milik banjar, desa, lembaga formal, maupun perseorangan. Jumlah tersebut masih ditambah lagi dengan banyaknya barungan gamelan Gong Kebyar yang tersebar diberbagai kota di Indonesia dan manca negara.
Di luar negeri, Gong Kebyar mula-mula dikenal lewat literatur dan rekaman. Salah satu rekaman itu adalah yang dihasilkan oleh Odeon dan Beka yang telah merekam gending-gending Gong Kebyar, seperti Kebyar Ding Sempati di Belaluan (Badung). Pada tahun 1931 Sekaa Gong Kebyar Peliatan mengadakan pertunjukan dalam rangkan Colonial Exposition di Paris. Lawatan sekaa ini dilanjutkan lagi tahun 1952 – 1953 ke Amerika Serikat. Kedua tour ini sudah tentu semakin menguatkan eksistensi gamelan Gong Kebyar di mata dunia.
Sampai dewasa ini Gong Kebyar selalu menjadi salah satu media dari diplomasi kebudayaan Indonesia. Adanya group kesenian dan gamelan Gong Kebyar yang dikirim dan ditempatkan di kedutaan negara sahabat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara di dunia.
Gamelan Gong Kebyar dapat berkembang dengan cepat serta mendapat apresiasi yang positif sampai dewasa ini, karena Gong Kebyar merupakan sebuah barungan yang praktis dan memiliki fleksibelitas yang tinggi. Penyajian Gong Kebyar memberikan ruang yang tidak terbatas bagi para pemainnya (seperti sekaa gong : anak-anak, wanita, remaja, remaja campuran, dewasa termasuk para werdha) untuk berkreasi, yang dapat memberikan sentuhan atraktif dengan penampilan yang lebih hidup dan dinamis.
Kelengkapan instrumen dalam satu barungan untuk gamelan Gong Kebyar tidak semuanya sama. Gong Kebyar dengan instrument yang paling lengkap disebut dengan Gong Kebyar Barungan Jangkep (Barungan Ageng) yang terdiri dari 21 jenis alat, masing-masing memiliki nama tersendiri dan fungsi tertentu terhadap barungannya, yaitu:
1. satu tungguh trompong, memakai 10 pencon
2. satu tungguh reyong, memakai 12 pencon
3. sepasang giying, memakai 10 bilah
4. dua pasang pemade, memakai 10 bilah
5. dua pasang kantil, memakai 10 bilah
6. sepasang kenyur, memakai 7 bilah
7. sepasang calung, memakai 5 bilah
8. sepasang jegogan, memakai 5 bilah
9. satu pasang kendang cedugan
10. satu pasang kendang gupekan
11. satu pasang kendang krumpungan
12. sebuah kajar
13. sebuah kempur
14. sebuah bende
15. sebuah kemong
16. sebuah kempli
17. satu pasang gong lanang-wadon
18. satu pangkon cengceng gecek
19. delapan cakep cengceng kopyak
20. dua buah suling kecil dan delapan buah suling besar
21. sebuah rebab
Secara musikal gamelan Gong Kebyar menggunakan sistem pelog lima nada, sama dengan sistem pelog lima nada pada jenis gamelan Bali yang lain, seperti gamelan Gong Gede, Gong Kebyar dan Palegongan, dengan urutan nada-nada seperti : nding, ndong, ndeng, ndung, dan ndang. Selain itu di dalam sistem pelarasan gamelan Bali ada istilah ngumbang-ngisep. Ngumbang-ngisep adalah dua buah nada yang sama, secara sengaja dibuat dengan selisih frekuensi yang sedikit berbeda. Kalau kedua nada pangumbang dan pangisep dimainkan secara bersamaan maka akan timbul ombak suara yang secara estetika dalam karawitan Bali merupakan salah satu wujud keindahan.
Di dalam Gong Kebyar juga dikenal konsep keseimbangan yaitu sikap hidup yang berorientasi pada “dualisme” baik dan buruk atau yang mencakup persamaan dan perbedaan. Konsep ini dapat dilihat dalam tema-tema kesenian Bali yang sebagian besar berangkat dari dualisme tersebut, sehingga muncul norma dan etika yang kuat dan menjadi bagian dari pertunjukan kesenian. Konsep keseimbangan yang berdimensi dua dapat menghasilkan bentuk-bentuk simetris yang sekaligus asimetris atau jalinan yang harmonis sekaligus disharmonis yang lazim disebut dengan Rwa Bhineda. Dalam konsep rwa bhineda terkandung pula semangat kebersamaan, adanya saling keterkaitan dan kompetisi mewujudkan interaksi dan persaingan. Keseimbangan dalam dimensi dua menjadi salah satu konsep dasar dalam musik Bali termasuk gamelan Gong Kebyar.
Hal ini tercermin dalam instrumen-instrumen Gong Kebyar umumnya dibuat dalam bentuk berpasangan ; lanang – wadon atau laki perempuan, istilah ini dipakai dalam penamaan kendang dan gong. Sistem laras ngumbang – ngisep ; nada yang sama namun dengan frekuensi yang berbeda. Unsur jalinan nada-nada atau suara dengan istilah yang bervariasi, seperti : kotekan, cecandetan, tetorekan dan ubit-ubitan. Teknik bermain kotekan ; menggunakan pukulan sangsih (yang jatuh diantara ketukan) dan pukulan polos (yang jatuh pada ketukan). Semuanya ini mengingatkan adanya unsur-unsur dalam keseimbangan yang tidak selamanya sejajar, tetapi dalam interaksi yang bersifat kompetitif.
Secara umum dapat diamati, bahwa struktur gending-gending Gong Kebyar terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu : kawitan, pangawak dan pangecet. Kawitan diibaratkan sebagai kepala, pangawak diibaratkan sebagai badan, dan pangecet diibaratkan sebagai kaki. Bagian-bagian ini diporsikan secara seimbang, dimana unsur rwa bhineda selalu tertanam didalamnya guna mewujudkan keharmonisan pada masing- masing bagian atau keharmonisan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Secara konseptual, kedua elemen ini menjadi dualisme yang selalu tercermin dalam aktivitas seni di Bali.
Garapan ini diciptakan pada tahun 2020 dalam rangka festival Ubud Performing Arts oleh dua seniman muda Dewa Ayu Eka Putri dan Ni Nyoman Srayamurtikanti.
Garba nenjadi awal terciptanya kehidupan. Sebuah ruang dimana semesta mikro terbentuk. Rahim perempuan tak lain adalah Brahman itu sendiri, Sang Pencipta semesta.
Garapan ini dipersembahkan pada seluruh rahim di semesta. Serta pada semua perempuan hebat di dunia. +
The Garuda Wisnu Kencana tells about the struggle of Lord Vishnu (Dewa Wisnu) who is assisted by the Garuda bird as his mount to seize Tirta Amerta (water of life) against the power of giants. Through a very deadly war, Tirta Amerta can be seized by The Lord Vishnu. The Tirta Amerta then is used to maintaining life. +
Gen merupakan pewarisan oleh satu individu kepada keturunannya melalui suatu proses penciptaan. Samahalnya dengan aksara menciptakan kata dan kata menjadi cikal bakal untuk menciptakan sebuah karya. Dari sinilah kelompok Bumi Bajra mengambil satu sisi pewarisan aksara, yaitu tradisi leluhur tentang mendongeng, menulis lontar dan tradisi lainnya yang dikemas menjadi teatrikal seni tari, musik dan vokal (kidung). +
Gender +
Sekar Gadung merupakan salah satu gending yang begitu familiar dan populer di antara gending-gending lainnya dalam repertoar Selonding Tenganan. Sekar Gadung merupakan gending yang menjadi basic dalam mempelajari Selonding Tenganan. Gending ini terbagi menjadi dua bagian yaitu Bagian pertama orkestrasi dengan tempo lambat dengan irama 1/8 dan bagian ke dua dengan tempo sedang dengan irama 1/16 atau ngucek.
Gamelan Selonding adalah alat musik tradisional Bali yang usianya lebih tua dibandingkan dengan gamelan-gamelan lainnya yang kini populer dalam kesenian maupun yang digunakan dalam upacara adat dan agama. Gamelan ini merupakan gamelan sakral yang digunakan untuk melengkapi upacara keagamaan (Hindu) di Bali. Persebaran Gamelan Selonding di Kabupaten Karangasem dapat ditemui di beberapa desa tua seperti Bugbug, Prasi, Seraya, Tenganan Pegringsingan, Timbrah, Asak, Bungaya, Ngis, Bebandem, Besakih, Selat. Dalam konteksnya dengan Desa Adat tersebut Gamelan Selonding ini digunakan untuk mengiringi prosesi upacara besar seperti Usaba Dangsil, Usaba Sumbu, Usaba Sri, Usaba Manggung dan lain sebagainya.
Kata Selonding diduga berasal dari kata “Salon” dan “Ning” yang berarti tempat suci. Karena dilihat dari fungsinya adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan atau disucikan. Mengenai sejarah munculnya gamelan Selonding belum bisa dipastikan namun ada sebuah mitologi yang menyebutkan bahwa pada zaman dahulu orang-orang Tenganan Pegringsingan mendengar suara gemuruh dari angkasa dan datang suara secara bergelombang. Pada gelombang pertama suara itu turun di Bungaya (sebelah Timur laut Tenganan) dan gelombang kedua turun di Tenganan Pegringsingan.
Gamelan Selonding terbuat dari bilah-bilah besi yang diletakkan dengan pengunci secukupnya diatas badan gamelan tanpa bilah resonan (bambu resonan). Suara yang ditimbulkan dari alat musik ini pun sangat khas dan klasik yakni gamelan berlaras pelog sapta nada (tujuh nada). Selonding biasanya disuarakan untuk mengiringi pelaksanaan upacara-upacara sakral dengan jenis gending yang berbeda, seperti Gending Geguron pada upacara sakral yakni : Ranggatating, Kulkul Badung, Kebogerit, Blegude, Ranggawuni.
Genggong adalah salah satu instrumen yang unik dan langka dalam karawitan Bali. Instrumen ini dikatakan unik karena terbuat dari pelapah enau (bhs. Bali pugpug). Di Bali penyebaran Genggong tidak sebanyak gamelan gong kebyar atau jenis gamelan lainnya, jumlah barungan Genggong di Bali yang saat ini diketahui adalah satu barung di Kabupaten Buleleng, tujuh barung di Kabupaten Gianyar, serta satu barung di Kabupaten Karangasem.
Dalam dunia musik, jenis instrumen ini dikenal dengan nama Jew’ s Harp. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Russia, India, Italia, serta Inggris, memiliki jenis instrumen yang mirip. Ada yang terbuat dari kayu, logam, bambu, dan perak. Selain di luar negeri, instrumen yang menyerupai Genggong juga terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Setidaknya tercatat lima daerah yang mempunyai alat menyerupai Genggong. Di daerah Yogyakarta disebut dengan Rinding, di Sulawesi Tengah disebut Embit, di Madura dan Bali disebut Genggong, sedangkan di Papua (khususnya di Suku Dani) disebut dengan Pikon.Genggong yang hidup di masing-masing daerah tersebut dimainkan secara solo maupun berkelompok. Ritme serta melodi yang disajikan disesuaikan dengan cara pandang musik di daerah budaya setempat.
Di Bali Genggong memiliki laras selendro. Meskipun nada-nada yang dihasilkan tidak sejernih dan sejelas nada yang dihasilkan seperti pada instrumen suling, namun rasa yang diciptakan masih bernuansa selendro. Genggong termasuk alat musik idiofon yang menggunakan tenggorokan manusia sebagai resonatornya. Pengaturan nada dilakukan dengan cara mengatur ruang dalam tenggorokan.
Salah satu desa di Gianyar yang memiliki group Genggong yang masih aktif adalah Desa Batuan. Saat ini Genggong telah mengalami perubahann dari instrumen tunggal (dimainkan untuk sendiri) menjadi musik kelompok (barungan). Perkembangan Genggong dari musik individu menjadi sebuah barungan gamelan tidak bisa dilepaskan dari perubahan konteks musiknya. Jika dahulu hanya digunakan sebagai alat untuk menghibur diri sendiri, kemudian berkembang menjadi ensamble untuk mengiringi sebuah bentuk pertunjukan. Sebagai sebuah seni pertunjukan, terdapat beberapa sajian dalam pementasan Genggong.
Struktur pertunjukan Genggong terdiri dari tabuh pategak, tari Sisia Pengleb, tari Onang Ocing, dan dramatari Godogan. Dari struktur pertunjukan tersebut, dapat dilihat bahwa gending-gending Genggong dapat dibagi menjadi dua, yaitu gending instrumentalia dan gending iringan tari.
Gending instrumentalia atau disebut juga dengan gending pategak adalah lagu-lagu yang biasanya dimainkan pada awal pertunjukan dan tidak terikat dengan tarian. Dalam pertunjukan Genggong di Batuan, terdapat beberapa jenis gending pategak, di antaranya Tabuh Telu, Angklung, Sekar Sandat, Sekar Sungsang, Sekar Gendot, Katak Ngongkek, dan Kecipir.
Jenis-jenis gending yang dimainkan juga mendapat pengaruh dari barungan gamelan Angklung. Gending-gending yang terdapat pada gamelan angklung di transformasikan melalui media Genggong. Hal ini masuk akal sebab antara Angklung dengan Genggong memiliki kesamaan laras, yaitu berlaras slendro. Oleh karena itu, terdapat juga beberapa gending Genggong yang diambil dari gending Angklung. Bahkan pada awal pembentukan ensamble Genggong, kendang yang digunakan adalah kendang Angklung. Jenis kendang berubah seiring dengan semakin kompleksnya tarian. Gending-gending iringan tari dimainkan untuk mengiringi tari Sisia Pengleb, Onang Ocing, dan Dramatari Godogan. Cerita ini mengisahkan tentang Raja Jenggala yang jatuh cinta kepada putri Daha.
Hingga saat ini, tidak diketahui sejarah pasti mengenai munculnya Genggong di Bali dan Batuan secara khusus. Menurut Pak Made Djimat (seorang maestro tari dari Batuan), berdasarkan cerita oral yang diturunkan kepadanya, disebut bahwa yang membuat Genggong adalah Tapak Mada (nama Mahapatih Gajah Mada ketika belum diangkat sebagai Mahapatih). Ketika Tapak Mada sedang berada di suatu hutan untuk membuat bendungan air, dibuatlah alat musik Genggong dan suling untuk mengisi waktu istirahatnya. Tapak Mada melihat sebuah pohon enau, kemudian dibentuk menjadi Genggong. Seiring dengan perjalanannya keliling Nusantara, Tapak Mada membawa kesenian ini ke Bali, begitu pula halnya dengan kesenian Gambuh. Namun, tidak diketahui secara pasti kapan Genggong muncul di Desa Batuan. Cerita ini didapatkan Djimat dari para sesepuhnya yang sering dipentaskan pada pertunjukan Topeng dan Prembon.
Saat ini I Nyoman Suwida adalah salah satu seniman asal Batuan yang paling getol dalam melestarikan kesenian genggong. Nyoman Suwida biasa memainkan instrument getar ini bersama penabuh lain yang tergabung dalam Komunitas Genggong Kutus miliknya. Komunitas seni ini, memiliki jadwal pentas yang padat, baik di desa tempat tinggalnya atau di luar daerah bahkan luar negeri. Jika pentas, paling tidak ada 3 jenis gending Genggong selalu dimainkan oleh Komunitas yang memiliki 15 anggota itu. Ketiga jenis gending itu, yaitu macepetan, sangkep enggung dan magenggongan. Masing-masing dari gending ini memiliki kekhasan, sehingga selalu menarik ketika dipentaskan.
Tari Genjek di Bali adalah tarian tradisional yang memadukan unsur seni vokal dan gerak dan masih berkembang lestari sampai saat ini di Kabupaten Karangasem, perkembangan hampir di seluruh wilayah kabupaten tersebut, yang cukup pesat di wilayah pesisir Timur diantaranya desa Jasri, Ujung, Seraya, Culik dan Tianyar.
Tari tradisional Bali ini lebih menonjolkan paduan suara kemudian diiringi dengan musik vokal yang meniru suara alat gamelan dikenal dengan toreng dan cipak, kemudian dipadu dengan gerak para penarinya, namun dalam perkembangannya diiringi juga oleh sejumlah alat musik, sehingga nilai estetika juga lebih menonjol.
Perpaduan oleh vokal dan gerak ini memang cukup menarik dan menghibur, para penarinya bisa menghibur dirinya sendiri termasuk juga orang lain yang menyaksikan.
Genjek atau megenjekan berasal dari kata gonna yang berarti gegonjakan, candaan atau senda gurau. Sejarah atau awal mulai dari tarian Genjek di Bali ini, tentunya berbeda dengan tari tradisional lainnya yang diciptakan oleh maestro seni.
Megenjekan ini berawal dari acara kumpul-kumpul setelah beraktifitas kemudian ditemani dengan tuak sejenis minuman beralkohol yang dihasilkan dari pohon lontar, kelapa ataupun enau.
Yang mana kawasan Bali Timur ini merupakan penghasil minuman tuak terbesar di Bali dan memiliki mutu terbaik, termasuk dalam perkembangannya sekarang ini tuak juga diolah menjadi arak dengan konsentrasi alkohol yang cukup tinggi.
Kumpul bersama sambil minum alkohol sejenis tuak ini dikenal warga sebagai tradisi “metuakan” tentunya kebiasaan seperti ini dilakukan oleh kaum laki-laki saja, semakin lama tentunya semakin hilang kesadaran alias mabuk, mereka mulai bernyanyi meluapkan kegembiraannya, diikuti oleh teman lainnya.
Akhirnya kebiasaan metuakan ini hampir pasti dibarengi dengan megenjekan atau tarian genjek tersebut, metuakan tanpa genjek terasa kurang pas. Akhirnya munculah grup-grup genjek menciptakan gending (nyanyian) dan akhirnya digunakan saat acara metuakan.
Beberapa group genjek juga menciptakan album genjek yang bisa didengarkan dan ditiru oleh setiap orang, sehingga nantinya bisa ditiru dalam setiap acara minum bersama dan tanpa dikomando akan diikuti oleh teman lainnya.
Tari tradisional Genjek di Bali merupakan tari pergaulan, sangat universal, sangat menyesuaikan dengan suasana dan perkembangan terkini, tidak terpaku pada gerakan atau olah vokal yang baku, mereka bebas berkreasi, seorang pembawa lagu (gending) bahkan bebas secara spontan menciptakan lagu sendiri atau mengenalkan lagu baru.
Tentunya menuntut kemahiran teman lainnya untuk mengikutinya dengan suara vokal yang sesuai termasuk kekompakan vokal pengiring. Dan sebuah kebanggaan jika mereka sanggup dan bisa kompak dalam mengiringi lagu yang dibawakan oleh pembawa lagu.
Tema lagu yang dibawakan biasanya berisi nasehat, rayuan, kritik, motivasi, pujian bahkan sindiran yang sangat komunikatif.
Dalam tari tradisional Genjek atau megenjekan iringan suara dan kekompakan vokal pengiring ini terasa lebih menonjol, terdengar saling bersahutan dengan ritme yang sesuai, kadang tinggi dan rendah, olah vokal pengiring ini sekilas seperti dalam tari Kecak ataupun Janger.
Tetapi dalam tari Genjek, tidak hanya menirukan suara “cak” saja tetapi olah vokal pengiring dikombinasikan dengan suara vokal menirukan alat gamelan lainnya.
Dari ritme yang diperdengarkan mengungkapkan kegembiraan dan memacu adrenalin setiap pesertanya untuk mendorong menari mengikuti irama dari suara genjek tersebut sehingga muncullah pertunjukan tari Genjek.
Tarian Genjek di masyarakat ini dimainkan oleh orang-orang yang suka minum, ditujukan lebih untuk menghibur diri mereka sendiri ketimbang untuk orang lain.
Acara minum atau lebih dikenal dengan metuakan walaupun yang mereka minum adalah bir atau sejenis alkohol lainnya dilakukan saat ada hajatan seperti acara pernikahan, acara 3 bulanan anak ataupun lainnya, lebih ke nuansa semarak dan pesta pora.
Minuman alkohol sejenis tuak adalah minuman yang sangat terjangkau bagi masyarakat kecil, yang efek mabuknya lebih keras dibandingkan minuman sejenis bir, sehingga tuak atau nama hitsnya adalah “lau” tidak bisa terlepas dari kehidupan para peminum.
Dalam perkembanganya tari tradisional Genjek di Bali ini berkembang cukup pesat, para penari genjek tidak harus mabuk terlebih dahulu dan tidak hanya oleh laki-laki saja, mereka juga memasukkan unsur wanita didalamnya sebagai pembawa lagu bersahut-sahutan dengan laki-laki, serta dipadu dengan iringan alat musik.
Sangat menonjolkan estetika dan juga etika, sehingga sangat menarik untuk dinikmati oleh orang lain atau yang mendengarkan, tidak seperti saat mabuk yang rentan hilang kendali lebih mengutamakan kesenangan sendiri.
Untuk melestarikan tari Genjek di Bali, kesenian tradisional ini juga kerap ditampilkan di Pesta Kesenian Bali di Art Center, salah satunya oleh Sekaa Genjek Kadung Iseng dari Desa Sraya Karangasem pada tahun 2018.
Gong Raja Due adalah seperangkat orkestra kuno yang disimpan di Pura Puseh Bale Agung Desa Adat Sepang, Kecamatan Busung Biu, Kabupaten Buleleng, Bali. Asal-usul gambelan ini tidak diketahui, tetapi gambelan ini telah dipentaskan pada saat karya tahunan di Pura Puseh sejak dahulu kala. Gambelan kuno ini hanya boleh dibunyikan ketika odalan oleh hanya delapan belas orang pilihan yang disebut Sekaa Gemblung.
Orkestra sakral Gong Raja Due ini terdiri atas sepasang kendang, sepasang gong, terompet kuno, dan sebuah alat dari besi yang diketuk untuk menentukan ketukan musik. Ada delapan belas jenis musik yang dimainkan dalam orkestra kuno ini. Delapan belas jenis musik itu sepintas terdengar sama, tetapi dapat dibedakan jelas dari suara terompet dan ketukan kendangnya.
Orkestra ini dipercaya dapat menghubungkan alam manusia dengan alam tak kasat mata, yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai alam wong samar. Tak hanya itu, orkestra ini juga dipercaya sebagai perwujudan dari dewata yang berstana di Pura Puseh, sehingga sebelum gong ini dimainkan, sebuah upacara penyucian harus dilakukan baik terhadap alat-alat musiknya maupun terhadap kedelapan belas orang pilihan yang bertugas memainkannya. +
H
Sampah yang kami kumpulkan selanjutnya akan dibawa ke pengepul untuk disalurkan ke perusahaan daur ulang. +
Komposisi musik Himpit lahir dari imaji dan kegelisahan dari komposer muda Mang Sraya. Karya ini hadir sebagai respon dari situasi terhimpit/terdesak yang dirasakan Mang Sraya ketika pandemi covid melanda dunia. Karya yang tergolong dalam musik kontemporer ini dimainkan secara solo dan mengandung banyak unsur improvisasi dari komposer. +